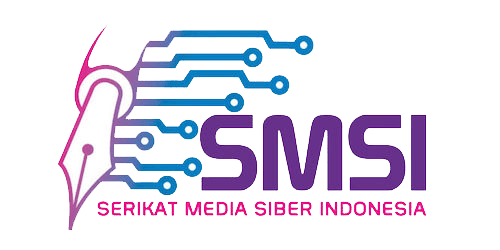Barometer Bali | Denpasar – Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dinilai tidak membawa perubahan berarti dalam praktik perlindungan hukum terhadap wartawan.
Hal ini disampaikan pengamat komunikasi publik, Emanuel Dewata Oja, menyikapi putusan yang diajukan komunitas Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) tersebut.
Menurut Emanuel, meski putusan MK patut diapresiasi sebagai langkah konstitusional yang menegaskan keberpihakan pada kebebasan pers, substansinya tidak menghadirkan terobosan baru.
“Saya tidak melihat adanya narasi atau dampak signifikan yang benar-benar memperkuat perlindungan hukum wartawan,” ujarnya di Denpasar, Senin (20/1/2026).
Wartawan senior yang akrab disapa Edo ini menjelaskan, putusan MK tersebut pada dasarnya hanya meluruskan penerapan UU Pers yang sejak awal kerap menimbulkan keraguan, khususnya terkait klaim sebagai lex specialis. MK menegaskan bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999.
Ia mengakui, secara teoritis UU Pers memang berprinsip lex specialis derogat legi generali (peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum).
Namun dalam praktik, regulasi ini justru sering diposisikan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir. Akibatnya, banyak sengketa pers tetap diproses melalui jalur pidana umum, bahkan berujung pada pemenjaraan wartawan atas tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah.
Edo yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali ini menilai persoalan utama selama ini bukan terletak pada kekosongan aturan, melainkan pada inkonsistensi penerapannya. Baik masyarakat pelapor maupun aparat penegak hukum kerap mengabaikan UU Pers dan regulasi turunannya.
Ia menambahkan, Pasal 8 UU Pers sebenarnya telah dipertegas melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 5 Tahun 2008. Aturan tersebut menyatakan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada wartawan yang menghasilkan produk jurnalistik sesuai kode etik dan ketentuan UU Pers. Sebaliknya, karya jurnalistik yang melanggar etika dan hukum tidak mendapatkan perlindungan.
“Sayangnya, aturan ini sering diabaikan. Putusan MK hanya menegaskan kembali hal yang sebenarnya sudah ada,” ujarnya.
Ketidakkonsistenan itu pula yang mendorong Dewan Pers menjalin nota kesepahaman dengan Polri pada 2023. Dalam MoU tersebut ditegaskan bahwa polisi wajib menempuh proses berjenjang dalam menangani sengketa pers, termasuk berkonsultasi dengan Dewan Pers sebelum melangkah ke proses pidana, agar mekanisme hak jawab dan hak koreksi dapat dijalankan.
Lebih jauh, Edo justru mengingatkan insan pers agar mewaspadai ancaman baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Sejumlah pasal, mulai dari penghinaan terhadap presiden dan pemerintah, penodaan agama, hingga penyiaran berita bohong dan tindak pidana siber, dinilainya sangat rentan digunakan untuk menjerat wartawan.
“Pasal-pasal itu sangat dekat dengan kerja jurnalistik. Pihak yang tidak suka pada pemberitaan bisa dengan mudah memanfaatkannya,” katanya.
Bahkan, ia menilai putusan MK berpotensi memunculkan konflik norma karena KUHP baru dinilai membatasi kebebasan pers, sementara UU Pers justru menegaskannya.
Di akhir pernyataannya, Edo menyoroti fakta bahwa tidak satu pun dari 12 organisasi wartawan dan media yang menjadi konstituen resmi Dewan Pers terlibat sebagai pemohon uji materi Pasal 8 UU Pers.
“Padahal mereka sangat berkepentingan. Dugaan saya, pola pikir mereka sejalan dengan pandangan kritis ini,” pungkas Edo. (red)